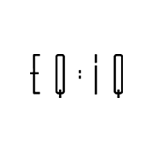 Ada sebuah cerita tentang perbedaan pemahaman tentang tipologi kecerdasan yang dijelaskan dengan lugas dalam sebuah buku best seller.
Seorang Ibu kepala sekolah menengah sedang membacakan nama-nama siswa
yang tergolong pintar dalam yudisium di sekolahnya. Seorang siswa
tiba-tiba bertanya, “Ibu siapakah yang lebih pintar, Albert Enstein atau
Mike Tyson? Rudi Hartono atau B.J Habibie?”. Kepala sekolah itu tidak
saja kaget, tetapi juga marah. Dengan suara tegas dan berapi-api, ia
berkata di depan pengeras suara, “Mana mungkin Mike Tyson yang kerjanya
hanya memukul orang dibandingkan dengan Enstein yang menemukan hukum
relativitas. Apalagi membandingkan Rudy Hartono dengan B.J. Habibie”,
lanjutnya. Penjelasan sederhananya seperti ini, mana yang lebih
diperlukan ketika seseorang mengalami kecelakaan dengan cedera berat
dikepalanya : seorang perawat lulusan akademi perawatan ataukah seorang
guru besar dan pakar ekonomi lulusan universitas luat negeri ? (Taufiq
Pasiak, 2002).
Ada sebuah cerita tentang perbedaan pemahaman tentang tipologi kecerdasan yang dijelaskan dengan lugas dalam sebuah buku best seller.
Seorang Ibu kepala sekolah menengah sedang membacakan nama-nama siswa
yang tergolong pintar dalam yudisium di sekolahnya. Seorang siswa
tiba-tiba bertanya, “Ibu siapakah yang lebih pintar, Albert Enstein atau
Mike Tyson? Rudi Hartono atau B.J Habibie?”. Kepala sekolah itu tidak
saja kaget, tetapi juga marah. Dengan suara tegas dan berapi-api, ia
berkata di depan pengeras suara, “Mana mungkin Mike Tyson yang kerjanya
hanya memukul orang dibandingkan dengan Enstein yang menemukan hukum
relativitas. Apalagi membandingkan Rudy Hartono dengan B.J. Habibie”,
lanjutnya. Penjelasan sederhananya seperti ini, mana yang lebih
diperlukan ketika seseorang mengalami kecelakaan dengan cedera berat
dikepalanya : seorang perawat lulusan akademi perawatan ataukah seorang
guru besar dan pakar ekonomi lulusan universitas luat negeri ? (Taufiq
Pasiak, 2002).
Kasus yang merupakan kisah nyata yang
sering kita lihat di lingkungan pendidikan nasional di daerah-daerah
ini, yang sering kita simak dimedia cetak ataupun elektronik membuka
mata banyak orang tentang kecerdasan. Apakah yang cerdas itu hanyalah
mereka yang pintar matematika dan bahasa ? fakta di lapangan menunjukan
bahwa orang yang kecerdasan intelektualnya (IQ) di atas banyak yang
kemudian menganggur, sementara orang yang piawai berolahraga justru
sebagian dari merekalah yang kemudian menjadi orang sukses dalam
pekerjaannya. Yang memiliki kecerdasan intelektual biasa saja, tergolong
lebih mudah bergaul, penolong sesama, bertanggung jawab, ramah dan
sebagainnya. Namun yang kecerdasan intelektualnya tinggi cenderung
kurang pandai bergaul dan egois. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi
mencapai perkembangan menakjubkan pada abad XXI ini. Hasilnya, beragam
budaya dan tata nilai menyebar cepat hanya dalam hitungan detik melalui
media televisi, internet, dan lain sebagainya. Terjadilah perubahan
sikap dimasyarakat sebagai konsekuensi kemajuan zaman.
Paradigma kecerdasan modern secara
bertahap mengalami perubahan yang sangat menggembirakan. Di awal abad XX
ditemukan konsep kecerdasan intelektual (IQ) yaitu kecerdasan seseorang
bisa dilihat dari hasil tes atau dikenal dengan istilah School Aptitude Tes (SAT)
dan menghasilkan kesimpulan bahwa tinggi rendahnya kecerdasan
intelektual sangat menentukan cerah buramnya masa depan seseorang. Intelligence Quotient
yang seratus tahun lalu diperkenalkan oleh William Stern telah menyita
perhatian yang tidak kecil. Kecerdasan hanya diukur dalam skor-skor
tertentu. Kecerdasan intelektual bahkan menjadi sesuatu yang takuti oleh
anak-anak yang memimpikan masa depan indah. Yang lebih tragis,
kecerdasan intelektual menghilangkan kesempatan bagi mereka yang
memiliki kecerdasan intelektual rendah, tetapi dengan kecerdasan lain
yang dominan.
Namun paradigma ini nampaknya harus
tergeser ketika fakta menunjukan bahwa kecerdasan intelektual tinggi
ternyata bukan jaminan bahwa seseorang dapat bertindak secara cerdas.
Terbukti, kasus korpsi, tindakan amoral, yang melanda daerah ini
sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan
intelektual tinggi. Kemudian ketika manusia menyadari bahwa banyak orang
yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi namun seringkali tidak
dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya, muncullah
pertanyaan, adakah bentuk kecerdasan lain yang berpengaruh dalam
menentukan kesuksesan hidup manusia ? dan ketika manusia menyadari bahwa
kesuksesan seseorang tergantung pada bagaimana caranya menghadapi dan
mengatasi persoalan hidupnya, muncullah sebuah keyakinan bahwa
kepiawaian seseorang dalam mengatur emosinya, berempati, beradaptasi dan
menemukan cara untuk menciptakan suatu kondisi yang mendukung bagi
dirinya untuk memudahkannya mengatasi persoalan adalah suatu bentuk
kecerdasan pula. Kecerdasan inilah yang kemudian disebut dengan
kecerdasan emosi (EQ).
Kecerdasan emosi yang diperkenalkan oleh
Daniel Goleman ini menyita perhatian kita tentang kecerdasan lain yang
dimiliki manusia. Paradigma kecerdasan intelektual sangat merugikan
manusia karena hanya sedikit manusia yang memiliki IQ tinggi. Menurut
berbagai penelitian, kecerdasan intelektual hanya berperan dalam
kehidupan manusia sekitar 20 %, bahkan hanya 6 % menurut Steven. J.
Stein, ph. D dan Howard. E. Book, M. D.
Kecerdasan emosi adalah kemampuan diri
untuk mendeteksi emosi diri sendiri dan orang lain. Emosi mempunyai
peranan penting dalam keberhasilan hidup manusia. Manusia perlu
mengelola emosinya yang berupa perasaan takut, malas, tidak percaya
diri, dan merubahnya menjadi berani, rajin dan percaya diri dalam
menghadapi hidup ini. Seseorang harus mampu mengembangkan kecerdasan
emosi dalam bertenggangrasa, berempati, jujur, tegas, dan lainnya. Semua
itu berhubungan dengan kemampuan mengenali dan mengelola emosi. Inilah
peran kecerdasan emosi. (EQ) (Khairul Ummah dkk, 2003).
Belum selesai kita membicarakan tentang
kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, kembali kita tersentak
dengan penemuan baru tentang kecerdaasan lainnya, Spiritual Quotient
(SQ). Kecerdasan spiritual yang dimaksudkan oleh penemunya Ian Marshall
dan Danar Zohar ini, melengkapi kecerdasan yang sudah dipelopori oleh
generasi sebelumnya.
Kecerdasan spritual yang dimaksud oleh
suami – isteri ini adalah kecerdasan menghadapi dan memecahkan persoalan
makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan hidup kita lebih
berarti dan bukan hanya sekedar mempunyai kecerdasan Intelektual tinggi
dan emosi yang baik, tetapi juga bisa memberikan arti dan jalan hidup
seseorang itu lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. (Danar Zohar
dan Ian Marshall, 2002)
Dalam kaitan ini, menurut ahli
Neuropsikolog Michael Persinger ditahun 1990-an dan yang lebih baru
temuan neurolog V.S Ramachandran bersama timnya dari Universitas
California mengenai adanya “titik Tuhan” (God Spot) dalam otak manusia.
Melalui pengamatan terhadap otak dengan menggunakan Topografi Emisi
Positron, area otak akan bersinar apabila subjek penelitian diarahkan
untuk mendiskusian topik spiritual. Bukti kedua adalah riset yang ahli
syaraf Austria, Wolf Singer pada era 1990-an atas The Binding Program,
yang menunjukkan adanya proses syaraf dalam otak manusia yang
terkonsentrasi pada usaha menyatukan dan memberi makna hidup. Suatu
jaringan syaraf yang secara literal “mengikat” pengalaman kita secara
bersama untuk “memaknai hidup ini”. Pada god spot inilah sebenarnya ditemukan fitrah manusia yang terdalam.
Di Indonesia, terutama kampus negeri
tidak ditekankan pada ajaran keagamaan. Para tokoh pendidikan di
Indonesia juga belum bisa mengubah sistem pendidikan ke arah pendidikan
akhlaq. Selama ini hanya pendidikan keilmuan saja. Tidak heran kemudian
banyak para intelektual yang korupsi. Di sini, nilai moralitas
keagamaan memainkan peranan penting.
Pendidikan agama Islam seharusnya
memberikan kontribusi yang jelas tentang makna hidup, tetapi pelajaran
agama Islam sekarang hanya dipahami sekedar ajaran ‘Fiqih’ semata.
Contohnya saja waktu penulis masih duduk di bangku sekolah dasar dan
menengah, mata pelajaran fiqih wajib dihapal. Misalnya menghapal rukun
iman, rukun Islam, tanpa dimaknai isinya, untuk apa kita shalat, apa
fungsi shalat, mengapa harus mengambil air wudhu dulu sebelum shalat,
dan sebagainya. Dampak “kegagalan” pendidikan yang demikian itu kini
sudah sangat kita rasakan. Pengangguran terus meningkat, moralitas
bangsa kian menurun, sikap saling menghargai sesama anak bangsa juga
semakin menurun. Bangsa ini kian dibanjiri manusia-manusia yang hanya
mementingkan diri sendiri dan manusia-manusia yang penuh kepura-puraan.
Di sinilah diperlukan implikasi kecerdasan spiritual dalam rangka
memperbaiki kualitas pendidikan kita saat ini.




0 comments:
Post a Comment